BAB 4
“MACAM mana kes hari tu?”
Mutiara meletak sudu di pinggan, air batu kosong dari
gelasnya pula disisip perlahan. Dengan
keluhan longgar, Ezeti seakan dapat
mengagak ada yang kurang enak. Dengan
sepasang matanya dia menumpu.
“Rupa-rupanya dia pernah didakwa
memberi keterangan palsu di mahkamah.”
“O?”
kaget Ezeti. Mata Mutiara ditangkap deras.“Keterangan palsu untuk
apa?”
“Masa bagi keterangan sebagai saksi.”
Mutiara menjungkit bahu dan mengeluh lagi
perlahan. Lama pula renungan mereka
bertembung, Ezeti menunggu. Berminat dia meski tiada kaitan
dengannya. Sekadar perhubungan longgar
antara mereka, dia tidak sepatutnya begitu prihatin. Tetapi dia gemar mendengar susur-galur
kerjaya mu selain simpati benar pada
wanita malang ditemuinya beberapa hari sebelum.
“Dia didakwa di bawah Seksyen 193
Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan akan dihukum penjara maksimum tiga
tahun dan denda.”
“Kenapa dia melakukannya? Mesti ada
sebab?”
“Soal punya soal, rupa-rupanya itu
cara dia hendak lari dari cengkaman suami yang menderanya zahir dan batin.”
Berkerut kening Ezeti.
“Dia menjadi hamba sex suami,
disewakan juga kepada lelaki lain oleh suaminya, penagih najis dadah.” Tampak kesal benar dia. “Lebih teruk lagi, suaminya selalu
menyalahkan nasib malang dia menyebabkan mereka hidup dalam kesusahan.”
Ezeti geleng perlahan. “Dari dulu
sampai sekarang, wanita selalu diperguna lelaki.”
“Itulah pasal. Selalu suami
menyalahkan isteri bila mala petaka diturunkan Allah. Tapi mereka tak sedar,
tanggungjawab melengkapkan keluarga adalah suami. Hem, sebab itulah aku tak
suka jantan.”
Ezeti tertawa perlahan. “Yang namanya jantan.” Sedikit keras namun nada perlahan. “Lelaki bagus…” merendah, memanjakan suara. Senyumnya terkulum, bersenda.
“Jantan dengan lelaki susah nak
bezakan kalau dalam kelompok manusia.
Kadang-kadang kita tengok dia macam lelaki, rupa-rupanya jantan yang
keparat.” Serius, nada bersenda.
Ezeti tertawa perlahan meski
kedengarankata-kata Mutiara serius.
“Sebenarnya cerita tadi rahsia, Ira
tak sepatutnya dedahkan kepada
umum.”
“Ala, aku tak akan bongkar rahsia ni,
sementelah aku kenal kakak tu dan aku bercadang nak tolong dia, jadiakukena
tahu kenapa dia begitu dan apa sebabnya.”
Mutiara mengangguk perlahan. Dia akui, Ezeti adalah penyelamat anak guamnya dari membunuh
diri serentak dengan anak-anaknya sekali akibat kekecewaan.
“Timbalan Pendakwa Raya yang
mengendali kes itu mengenakan ikat jamin RM3,000.”
“Dia bayar?”
Mutiara angguk perlahan. “Katanya hanya itu duit yang dia ada untuk
sara hidup anak-anak. Dengan menyerahkan
tiga ribu itu, dia dah tak berduit lagi untuk menyara hidup lima orang
anaknya. Sebab itu dia nekat merentap
nyawa semua mereka.”
Ezeti
mengeluh perlahan, menggeleng juga berkali-kali.
“Kenapalah suntuk benar fikirannya?”
“Dalam keadaan tertekan manusia akan
melakukan apa sahaja, lebih-lebih lagi yang rendah imannya.”
Ezeti
angguk, senyap. Menunduk dia
memain-mainkan ketul air batu di dalam gelas dengan batang strow.
“Begitulah nasib wanita selepas
berkahwin. Untung sabut timbul…”
“Untung batu tenggelam….” Ezeti
menyambung.
Tertawa mereka bersama,
perlahan. Tidak lama ledaknya, senyap
kembali. Ternyata tawa mereka tidak
berisi gembira, bahagia jauh sekali, sekadar bunga kemesraan.
“Kahwin pilihan orang tua barang
kali? Tak sempat mengenali hati budi bakal suami.”
Mutiara menggeleng keras. Berkerut juga keningnya. Ezeti
menunggu.
“Saling mencintai, kenal juga
lama. Suaminya berubah selepas diberhentikan
kerja.”
Mengeluh lagi Ezeti, sedih benar
dia. “Sekarang, kita boleh melawat dia?”
“Boleh rasanya. Ira dah beritahu dia, you kirim salam dan
bercadang nak melawat dia.”
“Eh, boleh tak kita jaga
anak-anaknya? Tak sampai hati biar
tinggal di rumah anak-anak yatim.”
“Ibunya masih dalam kes…” Mutiara
senyum sinis. “Budak-budak tu dilindungi
di bawah akta hak kanak-kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat.”
“So,
macam mana sekarang?”
“Mereka dilindungi sepenuhnya.”
“Selama-lamanya?”
Mutiara geleng.
“Sementara rawatan psikiatrik ke atas ibu mereka dilakukan dan
pendakwaan di mahkamah di atas percubaan
membunuh, selesai.”
“Sah dia gila?”
“Bukan gila, tapi gangguan fikiran
akibat tekanan emosi. Dia ingat semua
perkara, cuma sesekali akan hilang pertimbangan.”
“Kesian….”Ezeti mengeluh perlahan.
“Kalau you sayang dan kasihan,
jengahlah selalu. Bagi semangat, bagi
kasih sayang.”
Ezetiangguk perlahan.
“Anak-anak dia comel…”
Mutiara senyum lagi.
Mengangguk juga.
“Kalaulah aku dapat anak-anak seramai
itu, secomel itu, alangkah bahagianya.”
“Berangan untuk kahwin dulu,
baru berangan dapat anak.” Mutiara
menggiat.
“Tak payah kahwin tak boleh? Aku nak anak aja.”
Mutiara mengerling tajam.
“Yousempurna, kan? Jangan-jangan hormon
androgen tinggi tak?”
“Wei, semestinya aku wanita tulin. Berhormon estrogen dan progesteron, tau?”
“Habis tu, yang tak nak kahwin ni apa
pasal?”
“Engkau nak kahwinkah?”
Mutiara tertawa perlahan, menunjuk
rupa tidak berminat.
Ezeti menjungkit kepala, bertanya
dengan soalan berisyarat.
“Nak kahwin dengan siapa?” menurun intonasinya.
“Dengan lelaki, lah.”
“Nak cari yang namanya lelaki tu yang
susah.”
Ezeti tertawa perlahan, Mutiara turut tertawa.
Mengangguk Ezeti perlahan.
Kepada Mutiara diberitahu rancangannya untuk ke hospital, melawat wanita
malang yang diperkatakan mereka.
Katanya, selepas ke hospital dia akan ke rumah anak-anak yatim pula,
melawat lima beradik yang hampir menjadi mangsa
bunuh ibu sendiri yang tertekan fikirannya. Mereka nyaris maut selepas memakan makanan
yang sudah diracuni ibu sendiri.
“Sekarang cik peguam menangani kes
apa pulak, selepas berjaya kes tuntutan nafkah RM1 juta bekas isteri hartawan?”
Mutiara senyum senget, air batu kosong disisipnya
lagi.
“Zet berminat benar pada kerja Ira,
ya? Kenapa tak jadi peguam aja dulu?”Mutiara
seakan mahu memulang ‘paku buah keras’.
“Berminat tak semestinya nak
menceburi, sekadar tahu, pengetahuan am, kan?
Lagipun aku tak sepandai engkaudalam
memutar belit fakta.” Tertawa dia di
hujung sendanya.
“Hei, peguam tak semestinya pandai
membelit, yang penting, semangat menegakkan kebenaran dan membantu yang
teraniaya.”
“Semangat begitu pun aku tak
ada. Orang seni hanya tahu seni,
menghiburkan dan mengusik parasaan orang, juga keuntungan.” Tawa Ezeti
meledak. Mutiara turut tertawa namun dikawal, tidak setinggi
tawa Ezeti.
“Ira mewarisi bakat walid, aku macam umi. Sebuah kombinasi yang cukup baik.” Ezeti menyambung, Mutiara diam cuma.
Mengeluh dia dalam diam.
KUBAWA salam bulan dan catatan rindu
seorang penyair, ingin kuungkap kata cinta tapi kepada siapa? Ingin kulukis
lakaran kasih tapi potret yang mana….
Menggeleng dia berkali-kali.
Sudah lebih satu jam senaskah itu berpeluh dipegangnya, difahami
langsung tidak, dihafal jauh sekali.Peristiwa sepetang bersama Ezeti juga rancak bergentayangan, bermain tanpa
pengarah mahupun penerbit. Pelakonnya
hanya mereka bertiga. Meski ada
anak-anak kecil meriangkan namun dia bagaikan tuli. Rakan Ezetiitu juga yang
memenuhi, menggugah perasaan.Sudah berkali-kali dia terkenangkannya.
“Kenalkan, Mutiara.Ira, ini Neor.” Seringkas itu.
Dia
mengangguk cuma, manis senyumnya.
Sungguh menjaga santun dan pekerti, tidak seperti di kalangannya apabila
berkenalan, akan bersalaman dan ada kalanya bersentuhan pipi meski berlainan
jantina. Segalanya dikira Neor dalam
diam. Disisipkan renungan jauh ke salur
hati gadis itu. Menilik bagaimana
orangnya dari sudut pandangan mata hati.
Jelas punya seribu kelebihan, istimewa sungguh dia.
Mata terpaku terus melekat, bibir
berjaya mengorak senyum meski bergetar namun sempat dimaniskan. Sempat juga diajar jantung untuk berdegup
mengikut rentak biasa. Dipesan pada hati
agar bertenang dan bersabar….
“Hai, saya Neor, Mior RezamudinMior Ahmad.” Geruh suaranya. Dia sendiri mendengar kekalutan itu.“Panggil
saja saya Neor.” Bagai tidak berpuas
hati cara Ezeti memperkenalkannya kepada gadis itu, dia bertindak
memperkenalkan diri sendiri agar lebih lengkap, lebih padat.
Gadis itu sekadar senyum mengangguk
hormat. Manis sungguh, cantik sungguh dan
segala-galanya tersedia di seraut wajah lembut itu. Neor mengeluh perlahan. Empat puluh lima minit bersama bagaikan hanya
satu minit berlalu. Tidak ada lagi
perkataan yang cicir dari lengguk lidahnya, hanya bisu. Helaan nafas bagaikan mencekik khalkom, tidak
membenar dia menutur apa-apa. Hanya
mendengar perbualan dua sahabat itu.
“Terima kasih, jumpa lagi nanti,
assalamualaikum.” Kata-kata terakhir dia
kepada Ezeti pastinya namun Neor
mewakilkan dirinya mendahului.
“Ya, jumpa lagi,
waalaikumsalam…” manis senyumnya rasa
ikhlas sungguh.
Kesal juga tidak mengambil kesempatan
selama empat puluh lima minit itu sebaik mungkin.
Masih banyak masa lagi…. Pujuknya
sendiri. Direnung sekeliling ruang yang
lengang. Sudah kian sepi seruang kondorminium itu sesepi hatinya yang kosong. Sejak pertemuan dengan sahabat Ezeti
siangnya, sampai ke kelam malam itu, wajah manis yang sering menjelma dalam
hayal dan mimpinya kekal bergentayangan. Rindu kian memanas.
Dia kan kawan baik Zet? Esok lusa
ajaklah mereka keluar makan. Masih juga
mahu memujuk sendiri. Senyum lagi
dia. Wahai hati, sabarlah. Mungkin belum masanya, jodoh kan rahsia
Allah? Mengeluh lagi Neor, ringan lagi
dia dibawa merentas. Teringat kembali percintaannya
bersama yang tersayang lama dahulu.
Meski sudah berjanji untuk tidak mengenang dan mengingati apa yang sudah
ditinggalkan, sesekali sesat juga perasaannya. Yang itu, itu juga terkenang dan
dikenang.
“Nanti kalau dah pergi bandar, jangan
lupa kampung.”
“Mana boleh lupa, tempat jatuh lagi
dikenang…” senyum dia melirik ke
sebelah. Anak tangga rumah tua itu
sering menjadi tempat mereka bertenggek selain pangkin di bawah pokok jambu di
halaman. Sudah banyak janji setia
terakam di situ. Ibunya tidak melarang, menggiat juga tidak. Cuma pandai-pandailah menjaga maruah, katanya
selalu.
“Selagi bergelar umat Islam, bangsa
Melayu dan masyarakat Timur, maruah diri dan nama baik keluarga mesti
diutamakan.”
Dia dan buah hatinya akur
sentiasa. Tidak akan diizin orang ketiga
menghancur iman dan menggegar agama. Tidak juga mahu ada mata melihat mereka
sumbang, dia mahu orang melihat mereka sekadar sahabat karib.
“Awak nak kerja apa di sana nanti?”
“Kerjalah apa-apa pun asal halal.”
“Di sini juga tak kurang pekerjaan
yang halal…”
“Kat sana senang sikit nak dapat
peluang.”
“Peluang apa? Peluang jadi penyanyi?”
Dia sekadar tersenyum. Dia tahu, dia tidak pernah berjaya menyorok
dari gadis itu. Lamanya perhubungan
mereka dan eratnya silatulrahim, tidak membenarnya menjadi perahsia.
“Itu pun rezeki halal juga, kan?” bijak juga dia membujuk.
“Saya minat seni, menyanyi cuma loncatan,
saya nak mengetengah bakat saya mencipta lagu.
Banyak sudah lagu-lagu yang saya cipta tapi terus tersimpan. Kan baik kalau dapat saya manfaatkan?” dia nampak gadis itu mengangguk berkali-kali.
“Saya sokong minat dan kesungguhan
awak. Awak memang berbakat, pergilah
mencuba nasib.”
“Awak tak kisah kalau saya pergi,
awak tinggal di sini?”
“Saya dah besar, pandai jaga diri.”
Neor senyum cuma, jawapan yang
langsung tidak mengujanya.
“Lagipun apa nak takut, ini kan
kampung saya?”
Neor tertawa pula, ligat, lama tetapi
terkawal. Tawanya berbaki senyum
panjang.
“Bukan saya nak kata awak takut….”
Tawa gadis itu berbunga juga, mekar sudah
halaman perasaan disiram wangian juga. Ke
dua-duanya terhibur sungguh.
“Pergilah, tamat kontrak saya nanti, saya akan mencuba nasib bersama awak.”
“Betul?”
Anggukan gadis itu disambutnya.
“Saya bercadang, selepas tamat
kontrak, saya tak nak sambung lagi. Nak
cari kerja di bandar pulak. Sambil tu
nak sambung belajar.”
Bersetuju benar dia. Dalam hati bertaman rasa ria, pelangi diukir
bersama tasik madu, untuk menangguk secangkir manisan itu untuk si tuan puteri.
“Tak sayang tinggalkan kampung?”
“Nantipun kita boleh balik selalu,
kan?”
“Kita?” teruja lagi dia menangkap senyum si manis.
Telefon bimbit bernada singkat
memberi amaran ada pesanan ringkas, bolos, sekali gus merentap fikiran yang
melayang. Segera diangkatnya telefon di
sisi. Ditekan kekunci buka, disemak laman pesanan. Senyum dia berdengus perlahan. Hanya pesanan dari CELCOM. Dilepasnya semula telefon bimbit itu. Sedikit kecewa.
Sudah lebih 6 tahun berlalu namun pedih
semalam, sesekali masih terasa denyutnya dan kadang-kadang luka itu membuat dia
mengunci hati untuk insan lain.
Neor mengeluh perlahan. Gambaran gadis yang pernah menjadi pujaannya
direnung dalam samar perasaan. Sudah
lama dia tidak menatap seraut wajah itu, meski sekeping potret tidak dibenar
tersimpan. Tidak benci pada kenangan
lalu, cuma tidak mahu sebarang tanggapan serung dari sesiapa. Maka jadilah dia pungguk yang merindu bulan
di siang hari, malamnya pula dia menjadi buta. Akhirnya dia sekadar membayang bagaimana rupanya bulan itu.
“Di mana Fifei sekarang?”
Sebaik tersedar kelancangannya
menyebut seuntai nama singkat itu, dia menutup mulut. Beristighfar dia perlahan. Sudah 7 tahun aku belajar melupakannya, mana
mungkin malam ini menyebutnya semula!
Dia membentak sendiri. Sakit rasa
dadanya dik bentakan itu. Marah benar
dia. Mengeluh pula, berusaha merawat
kelukaan yang tiba-tiba. Semakin dirawat
semakin pula melarat sakitnya. Berdarah
pula. Lagi dia sesat ke lembah semalam….
“Selamat hari jadi, semoga hari ini
lebih baik dari semalam….” Segulung
kertas putih berikat reben berwarna merah dihulur.
“Apa ni?”
“Tengoklah sendiri.” Manis lagi senyumnya.
Segulung kertas berikat itu sudah
melonggar di jemari. Sekilas nafas dihela, terbentang sudah
sebuah potret berlukis pensil hitam.
“Cantiknya, terima kasih….” Dia hampir terjerit.
Fifei sekadar senyum. Manis sungguh, ikhlas benar dia.
“Berapa lama ambil masa melukis ni?”
Fifei
menunjuk dua batang jarinya yang ditegakkan.
“Dua hari?”
Dia angguk cuma.
“Wah, sesingkat itu?” teruja dia bakat yang dimiliki gadis itu.
“Terima kasih, potret ni lebih cantik
dari saya sendiri. Awak memang
berbakat.”
Fifei
mengucap terima kali lagi. “Nama
pun cikgu lukisan kan?”
Neor mengangguk faham. “Cikgu memang berbakat…” pujinya lagi sambil
mengusik. “Tapi tak kan nak jadi guru
sandaran dan guru ganti selamanya?”
“Dapat peluang nanti, saya pergilah…”
“Bagus, saya akan jadi guru
muzik.” Tawanya meledak sedikit
kuat.
“Tapi mengajar di institusi muzik,
bukan sekolah. Nak jadi cikgu sekolah, kena ada ijazahlah pula. Sedangkan SPM
pun cukup makan.” Lagi dia tertawa,
mengutuk diri sendiri.
“Cikgu juga namanya kan? Asal
didikasi, jasa guru sentiasa dikenang.”
Serambi rumah tua itu disemah
kuntuman bunga yang mewangi namun terkawal. Kembangan hanya berlengguk di
tangkai sendiri-sendiri, tidak langsung mencemar adap dan budaya.
“Kita warnai dunia ini dengan
seni-seni halus yang membahagiakan.”
Senyum ke duanya, mengangguk juga
bersungguh-sungguh. Hening sungguh petang yang dijejak menyusur senja. Makcik
Rominah tersenyum-senyum dari ruang tengah,
menggeleng juga perlahan sambil terus melipat pakaian yang diangkat dari
jemuran. Katanya dia tidak pernah curiga pada keakraban mereka selagi
pertemuan-pertemuan berlaku di hadapan matanya.
Neor dan Fifei sendiri selesa
berbual begitu dari meminggir dari mata khalayak. Mereka lebih gemar terbuka dan bersaksi juga.
“Saya nak fremkan gambar saya ni.”
“Up
to you, awak punya sekarang. Terpulang nak buat apa, asal jangan dibuang
atau dibakar.”
Dia tertawa lagi.
“Berapa hari cuti?” Fifei
menukar perbualan.
“Esok nak balik dah.”
“Sekejap je cuti?”
“Pemuzik kelab malam macam saya ni,
ada kerja ada gaji.”
Mengangguk Fifei perlahan, bersungguh-sungguh. “Berusahalah.”
“Awak tak jijik pada pemuzik macam
saya?”
“Kenapa saya nak jijik, seni itu
bersih, kan? Yang penting orang macam
kita mengekalkan kesucian itu.”
Senyum Neor berbunga senang.
“Beruntung saya dapat awak. Faham jiwa
saya.”
“Awak dah dapat saya ke?” berkerut keningnya, dalam senda dia serius.
“Awak, jangan cakap macam tu. Saya
sungguh-sungguh cintakan awak.” Dia
sedar, saat itu dia sangat-sangat emosi.
Melihat seriusnya Fifei, dia menjadi takut akan kehilangan.
“Fi,” rasa
gementar dadanya mahu menyudahkan nada bisikan serius itu.
“Kita bertunang?” lagi memperlahan intonasi. Tidak mahu ada
yang lain mendengar.
Kedengaran tawa Fifei melantun sedikit kuat, ditutup mulutnya
dengan tangan kanan. Merah juga mukanya mungkin mengawal malu.
“Apa yang riang benar berdua
ni?” tiba-tiba ibunya muncul membawa
sedulang hidangan ringan. Rupa-rupanya
sewaktu dia menghilang selepas selesai melipat pakaian, ibunya menyediakan air
pambasah tekak.
Fifei
pantas bangun, senyum masih berbaki.
Dulang air bujang disambutnya lalu diletak di atas meja hidang di
hadapan mereka.
“Tak payah susah-susah Mak Ro.”
“Tak susah mana, air bujang aja.” Makcik
Rominah meletak punggung.
“Mak, kalau kami bertunang, mak
setuju tak?”
“Reza…” Fifei
menolehnya dengan kening berkerut.
Malu pastinya.
Dia tidak mempeduli, Makcik Rominah juga direnungnya mengharap kepastian dan
persetujuan.
“Kena hantar wakil merisik dulu. Tapi Fifei
dah bersediakah?”
“Saya masih nak sambung belajar. Kerja tetap pun tak dapat lagi.” Ada manis di wajahnya walaupun jawapan di
bibirnya memberi maksud menolak.
Makcik Rominah menangkap sinar mata Reza.
“Lepas bertunang boleh juga belajar,
kan mak?” dia masih bertawar-menawar.
“Mak saya mesti tak benarkan…” sayu rintihnya, Neor faham. Orang tua
Fifei sudah dikenali
keperibadiannya. Pada mereka, pelajaran
perkara utama.
“Beginilah, Reza ada cita-cita, Fifei pun ada cita-cita. Tak perlulah bertunang dulu, dah cukup duit,
dah tamat belajar, kahwin aja.”
“Awak tunggu saya?” dia mahu Fifeinya bersumpah setia bersaksi ibunya. Mahu bertunang cara begitu.
Fifei
rupa-rupanya bersetuju sangat.
Perjanjian tercipta bersaksi wanita separuh usia itu. Tidak langsung malu mereka memeterai janji
sementelah Makcik Rominah cukup
memahami dan benar-benar menyenangi persahabatan yang terjalin sejak zaman
kanak-kanak. Seutas rantai emas putih
halus, berhias sebiji berlian kecil dihulur kepada ibunya.
“Reza
belinya masa dapat gaji pertama.”
Makcik Rominah menyambut, dibelek sekilas sebelum beralih
kepada gadis yang sudah senyap di sebelahnya.Neor di hadapan mereka hanya menghidang senyum
manis.
“Untuk Fifei?”
Neor mengangguk. Ibunya turut mengangguk lalu menyerahkan
kepada Fifei.
“Abang Reza bagi sebagai tanda.” Disimpankannya ke dalam tapak tangan Fifei.
Fifei
membelek pula. “Tak perlulah bagi
apa-apa…”
“Ambillah, Reza ikhlas.”
“Untuk mak?” Fifei
menoleh Neor pula, mungkin berasa ragu menerima pemberian semahal itu di
hadapan ibu itu.
“Mak pun dia belikan juga, ini
ha.” Seutus rantai emas kuning di
lehernya ditunjukkan.
Fifei
berpuas hati dan mengucap terima kasih, bersungguh-sungguh benar.
“Lepas ni saya akan
bersungguh-sungguh bekerja untuk kumpul duit banyak-banyak.”
Mengangguk-angguk ibunya,
bersetuju. “Lelaki mesti ada kerja
tetap, rumah, kenderaan, sebelum meminang anak dara orang. Barulah orang tak ragu-ragu serahkan anak
mereka.” Ibunya menambah semangat.
“Hah.” Terhambur dengusan keras. Marah pada rakusnya perasaan membawanya
mengutip kenangan indah itu. Sudah lama
kenangan itu tidak melintas, sudah diajar hati agar tidak terhanyut. Tidak sudi
lagi dia mengenang silamnya tetapi sejak akhir-akhir, Fifeinya seakan
dekat. Sudah sering muncul bertamu di
dalam hati.
Ditongak frem gambar yang dilukis
buah hatinya, direnung lama. Setiap hari
akan dilakukan begitu, tidak langsung jemu dia.
Rindupun bertaut. Malam itu
berlainan benar perasaannya. Hairan
benar dia.
Telefon dicapai, nombor telefon Ezeti dicari laju. Ditekan kekunci panggil dan
menunggu dia untuk beberapa detik yang singkat.
“Zet, saya nak kenal kawan awak tadi, boleh?” lancar benar ungkapannya disudahkan dengan
senafas yang singkat juga.
“Tadi bukankah dah kenal dia?”
berbaul nakal.
“Saya nak kenal rapat…”
“Apahal ni?” lagi seakan bersenda. Neor sudah faham maksud gadis itu.
“Tolonglah…” keras benar bunyinya membuat Ezeti di talian tertawa kuat.
“Sebenarnya saya dah pernah nampak
dia sekali masa kita minum di restoran hari tu. Itulah perempuan yang awak
perolokkan saya.”
“O, dah tangkap cintanlah ni?”
Neor senyum dan tertawa perlahan.
“Awak dah lupakan kekasih awal dan
akhir awak ke?”
Neor terpukul. Benar-benar terhenyak. Potret sendiri dalam bingkai di dinding, ditongak
lagi.
“Yang berlalu sudah saya biarkan
berlalu, tak guna dikenangkan lagi…”
sedikit beremosi jawapannya meski seakan bersenda.
“Tapi awak pernah baritahu saya,
tidak mungkin ada yang lain akan menempat di hati awak selepas perpisahan
pertama dengan orang pertama?”
“Saya nak mulakan hidup baru. Awak
selalu nasihatkan saya supaya melupakan hitam semalam, kan? Awak kata, yang pahit boleh dimaniskan asal
kita berusaha. Sekarang saya nak
berusaha menjadikan hidup saya manis.”
“Ya, memang saya suruh awak begitu,
tapi sekarang, saya tengokawak macam sebaliknya.”
“Saya macam mana di mata awak?”
“Macam dah gila bayang.”
“Hei! Jangan serkap jarang.”
Ezeti tertawa sedikit kuat.
“Kerana nak melupakan semuanya maka saya
nak mengisi kekosongan hati saya…”
“Itu saja sebabnya? Nak memperjudikan Ira ke?”
“Zet, hati saya dah terbuka untuk
mencari pengganti. Kebetulan saya
benar-benar tergoda dengan dia. Jadi,
salahkah saya mencuba nasib?” sayu dan
mendayu bunyinya. Memang dia ingin
merayu….
Ezeti tertawa lagi. Kuat dan semakin kuat, berlangsung sedikit
lama.
“Kenapa awak ketawa? Gila dah?” Neor serius.
“Kelakar.”
“Apa yang kelakarnya?”
“Kelakar sebab awak cuba nak tipu
diri awak sendiri dan berusaha untuk menipu saya.”
Neor terdiam, senyap. Menyesal dia menggunakan Ezeti untuk mengenali gadis itu lebih rapat. Rasa benar-benar dimalukan. Meski terhenyak namun tidak mungkin dia berundur.
“Bahagian mana dia macam Fifei?”
“Saya tak kata mereka serupa?”
“Tak mungkin awak akan jatuh cinta
pada yang tidak ada kaitan dengan cinta pertama.”
Neor mengeluh perlahan. memang tidak mungkin dibohongi sahabat
karibnya itu. Dan memang dia hanya akan jatuh
cinta pada gadis yang punya ciri-ciri seperti kekasih pertamanya.
Ezeti
tertawa lagi. Tawanya sungguh
melukakan. Neor berasa sangat-sangat
disakiti.
“Di mana awak kenal Fifei?” mahu marah tetapi tidak ditemui rasa marah. Mahu mengherdik namun tidak dipelajari ilmu
begitu. Akhirnya perlahan disoalnya Ezeti.
“Dari dalam diri awak.”
Neor
mengeluh perlahan. Jelaslah, Ezeti
memang sahabat. Dia bukan sahaja rakan
seperjuangan tetapi benar-benar sahabat
sejati.
“Zet, saya dah berjaya melupakan semuanya, tolong jangan
kembalikan memori itu. Jangan dipanaskan
semula semangat lama saya, saya tak nak ingat lagi semua itu….” Merintih dia, panas kulit wajah, diraup
berkali-kali.
“SorryNeor.” Mendatar dia bernada kesal. “Saya berusaha untuk bersenda, tak sangka awak
serius malam ni. Kenapa emosional sangat
ni? Semangat malam?”
“Boleh tak, saya kenal dengan kawan awak
tu?” itu juga pintanya.
“Boleh, apa salahnya.”
“Dia belum kahwin, kan?”
“Belum.”
“Balum bertunang?”
“Belum.”
“Hatinya belum berpunya?”
“Hei, itu awakkena tanya dia sendiri.
Saya tak tau hatinya sebab tak nampak di mata.”
“Kan kawan baik awak? Tak kan awak
tak tahu?”
“Tak tahu.”
“Bohong.”
“Kami berkawan cara professional. Hal peribadi tak pernah saya bertanya dia.”
“Tak pernah dengar dia bercerita
pasal teman lelakinya?”
“Teman lelaki dia adalah saya, teman
wanita pun saya.” Tertawa lagi dia.
“Baiklah, kalau begitu, awak tolong
bagi nombor telefon dia, nanti sayacalldia,
tanya sendiri.”
“Amboi, nekatnya?”
“Saya tak boleh tunggu lagi.”
“Dah angau dah?”
Neor tertawa perlahan.
Semoga mentari yang terbit esok,
membawa kepanasan yang bisa membakar semula semangatnya yang semakin mendingin. Pesanan ringkas Ezeti yang mencatat nombor telefon yang dipinta dibaca pantas. Ditekan nombor telefon itu, juga pantas. Dia menunggu
lama, langsung tiada jawapan. Dua
kali dicuba, akhirnya dia mengalah. Mengeluh dia perlahan, nekat menunggu hari
siang untuk meneruskan hasrat.




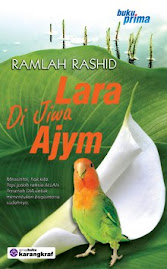




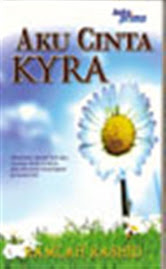.jpg)

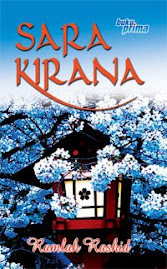
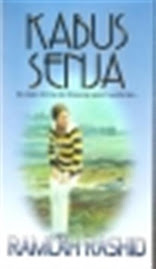+(Large).jpg)

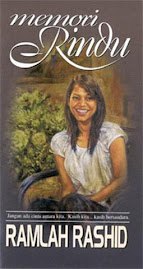.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment