BAB 3
SEMAKIN jauh meninggalkan siang,
semakin sepi, semakin sayu dan semakin pilu dia. Makcik Rominah dan Rafiq sudah lama tenggelam
pastinya, hanyut dibuai mimpi indah masing-masing. Hanya dia sendiri takut benar untuk dibuai,
takut mimpi semalam menghantui. Seusai makan malam bersama ibunya, dia
menyelinap ke bilik. Sudah lama benar
bilik kecil itu tidak dihuninya. Meski
usang namun kekal menyimpan momen silam penuh duka dan air mata. Sedikit benar
suka dan tawa ria. Mengeluh dia seraya
menyemah sekeliling. Kekal sama,
bisiknya perlahan. Meski sudah lama
benar tidak di situ, kekal terurus rapi.
Mesti mak membersih dan mengemasnya
selalu. Terkasima dia keperihatinan
Makcik Rominah yang tidak pernah berubah.
Mungkin mak rindu aku selalu. Pilu pula hatinya. Terakhir pulang, enam bulan dahulu. Tidak bermalam, tidak juga menjengah ke bilik
itu. Hanya menyinggah seketika sewaktu
dalam perjalanan dari Utara menuju ke Kuala Lumpur sehabis pengambaran
drama. Duduk hanya hampir dua jam
bersama Makcik Rominah, mandi bertukar pakaian, dia pamit. Sibuk alasannya. Memang dia sibuk benar…
Makcik Rominah tidak pernah membantah
meski anak seakan kunjung bertandang, persis tetamu yang datang dan pulang
selepas minum secawan kopi. Makcik
Rominah tetap riang, melayan selayak anak kesayangan.
Mak memang wanita hebat, tidak pernah
menunjuk rupa duka, kecewa juga tidak.
Mustahil mak tak pernah rasa sedih disisih anak-anak yang
didewasakannya. Tak mungkin. Menggeleng dan mengeluh lagi.
Dari melangut di tingkap bilik yang
terbuka luas, mendongak angkasa melihat bulan separuh, beralih dia duduk di
lantai bersandar pada katil. Tingkap
sudah ditutup rapat, dikunci juga.
Mendongak pula dia, menujah lampu bulan kekuningan. Masih seperti lampu lama dahulu. Itu perkiraannya di dalam hati.
Sewaktu zaman kanak-kanak, di situ
dia berkongsi bilik bersama Rafiq.
Setelah berganjak kanak-kanak remaja, Rafiq mendinding ruang lain untuk
dijadikan bilik sendiri. Tidak gemar
berkongsi bilik bersama adik itu.
Teringat dia kejadian di suatu malam, peristiwa besar yang benar-benar
memunahkan perasaannya. Semangatnya bagaikan dibunuh mati. Berakhir sudah baki kasih dan sayang antara
dia dan Rafiq malah yang tinggal untuk
Meor Razak hanya hormat serta tanggungjawab.
Bersyukur diamasih ada dua rasa
itu.
“Ayah, tengok yah. Gitar!”
Panas wajahnya seluruh darah tumpah
sudah. Di hadapan matanya, Rafiq
membunuhnya kejam. Seusai makan malam,
Rafiq berlari dari bilik mereka membawa gitar yang disembunyikan. Sudah dua hari alat muzik itu di situ,
dipetik apabila tiada sesiapa di rumah, akhirnya berjaya dikesan Rafiq. Lalu
gitar itu menjadi senjata pemutus kasih sayang dia dan ayah mereka.
“Dari mana kamu ambik barang syaitan
ni?” herdik Meor Razak sudah cukup
menggegarkan jantung.
“Bawah katil, Rafiq baru
terjumpa.” Adunya bangga benar.
“Siapa punya gitar ni?” seperti guruh derasnya dia menengking.
Dia terus bungkam, angguk berasa
berat, geleng berasa ketat. Tunak mata
sahaja berbahasa bisu, melihat gitar yang sudah di tangan lelaki perkasa itu. Lelaki paling tegas dalam pendidikan
anak-anak, seluruh kampung tahu itu, kagum semua dan tunduk hormat.
Makcik Rominah berlari dari dapur,
pasti mahu menjadi orang tengah. Memihak
anak dan memihak suami juga, begitu seringnya.
Namun sikap baran suami sering menewaskan kasih ibu terhadap
anak-anak. Sudahnya hanya air mata berderai,
lemah juga perasaan Neor. Tidak sanggup
melihat Makcik Rominah menangis sedih.
“Siapa punya? Mengaku cepat!” bagaikan
runtuh rumah pusaka itu dik kerasnya lantunan suara Meor Razak. Runtuh juga hati Neor.
“Ya Allah, kenapa ni? Malu kalau orang dengar.”
Makcik Rominah menekan suara, cemas benar. “Rendahlah sikit suara abang.” Begitu permintaannya sering kali.
“Ni, tengok anak-anak awak. Tengok!”
gitar di tangannya ditunjuk-tunjuk.
“Apa perkara yang anak-anak abang
buat sampai abang menjerit-jerit begini?”
sudah terang lagi Makcik Rominah bersuluh. Sering begitu demi mencari helah,
memperlengah-lengahkan demi mencari akal sendiri untuk mencantas.
“Ni, siapa punya ni? Siapa punya barang maksiat ni!” diulang soalan sama, ayat juga hampir sama.
“Gitar siapa Rafiq? Siapa punya?”
lembut juga suara Makcik Rominah, tampak gementar benar ibu itu. Di tengah rumah, di halaman biliknya empat
orang berdiri dengan berlainan emosi pastinya.
Ria di hati Rafiq dik baran Meor Razak,
ketakutan di hati Neor dan Makcik
Rominah. Sudah dapat dijangka dan dibaca
Neor.
“Mak tanyalah Reza, siapa dalam rumah
ni yang siang malam berangan nak jadi pemuzik, nak jadi penyanyi?”
“Siapa punya Reza? Siapa punya kamu bawak balik, nak?” lembut juga ibu itu.
“Mesti dia bazirkan duit, beli
gitar. Bukan beli buku.” Semakin pedas cili yang ditanam di lidah
Rafiq. Memang begitu selalunya, diaakan
menyimbah minyak apabila ayah mereka
mahu membakar.
Neor diam juga, tunduk terus bisu.
“Siapa punya?!” lagi suara Meor Razak merentap jantungnya. “Kamu beli guna duit yang aku bagi ya? Dengan
duit belanja?”
Terhenjut bahu Neor diherdik teruk
begitu.
“Shamsul anak Pak Daud punya.” Terpaksa dia menjawab meski takut benar.
“Kenapa ada di sini? Kenapa bawak balik!?” juga tinggi.
“Reza nak berlatih, nanti Reza dengan
Sham nak buat persembahan di sekolah, Hari Guru.”
“Main muzik? Nak main muzik?” sudah dihempuk gitar berwarna hitam itu di
tiang seri rumah. Bukan sahaja
menggegarkan rumah tetapi menusuk ke jantung Neor juga. Hening awal malam sudah tidak indah
lagi. Geruh lagi membingitkan.
“Ayah, jangan…” meluru dia mahu menyelamat gitar yang bukan
miliknya.
“Jangan.” Sudah dipegang namun Meor Razak lebih perkasa
dengan kuasa seorang ayah. Ditolak dia
ke dinding, tercelepuk jatuh. Dik
kuatnya hentakkan tubuhnya, al-quran yang bersusun di atas para di dinding
jatuh menimpa kepala.
“Ya Allah anak aku.” Makcik Rominah meluru. Dia dapat merasakan tangan ibu itu mengusap
dan menggosok kepala yang sengal, sakit dihimpap senaskah al-quran berkulit
keras. Matanya sudah sedikit kabur, pening.
“Pantang keturunan aku, ahli
muzik. Pantang aku!”
“Abang, budak ni bukan nak jadi ahli
muzik, cuma nak main di sekolah aja, nak raikan cikgu-cikgu dia. Apa yang kecuh sangat?” masih berani ibunya menjawab.
“Mula-mula main untuk suka-suka di
sekolah, lepas tu seronok, melahu ke sana, melahu ke sini dengan gitar. Tak kira waktu Maghrib, tak kira tengah
malam, duduk di simpang-simpang, main gitar.
Melalak menyanyi. Dah seronok
lagi, pergi ke kelab-kelab malam main muzik, cari betina keberet!”
“Apa benda yang abang melalut sampai
jauh benar? Marah sikit-sikit sudahlah.”
“Ah! Aku tak kira. Dah aku kata, apa saja benda yang berkaitan
dengan muzik, aku haramkan masuk ke rumah ni. Kalau kamu masih nak jadi anak
aku, ikut peraturan aku. Kalau tidak, pergi cari bapak lain! Pergi!”
Dia kekal membatu, tidak langsung
berniat untuk meninggalkan rumah itu, lebih-lebih lagi ibunya.
Meor Razaksudah menghempuk gitar
beberapa kali. Dari patah dua, patah
tiga, hacur akhirnya. Dari dinding itu
dia melihat hatinya dilumati lelaki itu.
Pesanan Shamsul supaya menjaga gitar kesayangannya sebaik mungkin,
bagaikan menikam mati dia.
“Anak orang lain naik pentas ambik
hadiah, kamu naik pentas petik gitar? Anak orang lain naik pentas baca
al-quran, jadi qari, kamu melalak menyanyi, main gitar? Di mana aku nak letak muka? CucuLebai Meor jadi
ahli muzik, jadi penyanyi! Di mana aku
nak letak muka? Cukuplah seorang dalam
keluarga Lebai Meor menconteng arang.”
“Abang! Sudahlah. Kalau dah mula
bercakap, awak akan ungkit sana ungkit sini.
Marah seorang aja tak boleh ke?”
“Memang dasar keturunan…”
“Sudah, saya kata. Kalau awak nak ungkit lagi, saya dengan Reza
akan keluar dari rumah ini malam ini juga.”
Makcik Rominah sudah menarik tangannya, mahu dibawa ke pintu namun, dia
berkeras.
“Mak, jangan.” Geleng dia, memujuk Makcik Rominah, tidak
mahu emaknya menjadi isteri derhaka.
“Keluarlah, keluar. Sekali kamu keluar, jangan kamu balik-balik
lagi. Tak ingat peristiwa 16 tahun dulu?
Tak ingat?” sudah tidak menengking,
suara Meor Razak seakan berungut perlahan.
Dia pula sudah meraung, tidak
mempeduli tawar-menawar orang taunya. Sama tingginya pula dengan ceceran leteran
Meor Razak, sudah tidak ada malu dan segan lagi, menangis, mendendangkan suara
yang sudah mulai berubah dewasa.
Seingatnya sejak kanak-kanak sehingga berusia enam belas tahun itu,
tidak pernah dia menangis begitu. Malam
itu kelelakiannya tercabar sudah. Sedih
dikasari Meor Razak, sedih gitar berkecai dan bimbang Shamsul kecewa gitar
miliknya rosak di tangan orang lain.
Semuanya beraduk membuatnya sekecewa itu.
Makcik Rominah sudah mengutip
senaskah al-quran di lantai, digenggam erat, dicium, dijunjung, diletak ke
dada. Begitu mereka diajar menghormati
kitab suci itu. Diletak ibunya kembali
ke atas para. Selesai kerjanya, dia
dipegang, dibantu bangun dibimbing masuk ke bilik.
“Diam! Kenapa kamu menangis di situ?
Apa, emak bapak kamu dah mati dan kamu dah tak reti mengaji untuk mak bapak
kamu?” ayahnya mengherdik semula.
“Dasar anak tak tahu diuntung.” Perlahan ungkapnya hampir tidak didengar Neor
buah butirnya. Hanya tahu ayah itu masih
belum puas marah namun, Makcik Rominah jelas.
“Sudahlah abang, awak ni kalau
marah?”
“Kenapa kalau aku marah? Tak betul
tindakan aku? Salah apa aku cakap?”
sudah kembali menengking.
“Bukan salah, tapi cara marah tu
beringatlah sikit. Jangan sampai cakap
yang bukan-bukan.”
“Awak diam, nanti dengan awak sekali
aku halau. Pergilah dua beranak main
muzik di tepi jalan. Ikut…”
“Abang!” sudah meluru Makcik Rominah, menahan maranya
kata-kata akhir suaminya yang tergantung, tidak sempat disudahkan.
Pantas juga Neor memegang tangan
ibunya, menggeleng dia tidak gemar ibunya bertikam lidah lagi. Marah ayahnya sudah bukan seperti selalu,
sudah berlainan benar. Dia berusaha
bangun, mahu bercerita duka di dalam bilik.
Terasa bergetar dingin jemari Makcik Rominah memegang bahu dan
lengannya, membimbing. Dibiarkannya.
Ayahnya dan Rafiq sudah menghilang,
entah di mana dua lelaki itu, malas difikirkan.
Biar.
“Mak, gitar Shamsul. Esok persembahan, Reza nak main apa? Nak jawab apa kat Shamsul?”
“Bila nak mainnya?”
“Petang esok, pukul dua.” Kepada ibu itu dia mengadu. Dilihatnya merah mata Makcik Rominah beranak
air juga.
“Kenapa tak bincang dulu dengan ayah,
Reza nak main muzik untuk acara sekolah.
Untuk majlis Hari Guru.”
“Kalau ayah tahu awal, ayah bagi
ke?” jengkel dia, menyindir.
“Kalau ayah tahu awal, tidaklah ayah
marah sangat. Kalau ayah tak benarkan, tak payah bawak balik gitar orang.”
Tidak berupaya dia menjawab apa-apa,
terkunci sudah.
“Macam mana ni?” itu juga ditanyanya,bukan menyoal ibu itu
tetapi kepada diri sendiri. Buntu sudah
dia.
“Nantilah, mak fikirkan. Sekarang ni rehat dulu, tidur.”
“Macam mana nak tidur, Shamsul sayang
sangat gitar dia. Gitar tu bapak dia
hadiahkan sebab dia menang berpidator.”
Kedengaran nafas Makcik Rominah
mendesah keras. Menelan hiba pastinya,
tidak dipedulikan. Tidak mahu memujuk
ibu itu sedang hatinya sendiri tidak terpujuk.
“Sudahlah, selagi dunia belum kiamat,
kita masih ada usaha. Tidur dulu. Esok kita fikirkan jalan untuk menyelesai.” Terasa suam bibir Makcik Rominah menyinggah
dahi dan pipinya, dia dicium ibu itu.
Terpujuk sedikit dia.
Erat dia memeluk Makcik Rominah, mahu
sepuasnya menangis, esok dia tidak mahu menangis lagi. Dakapannya dipererat Makcik Rominah,
ditepuk-tepuk dan digosok-gosok juga dia perlahan.
“Sudahlah, jangan dendam ayah, tak
mencium bau syurga.”
“Bapak boleh je buat sebarangan pada
anak?” diluah keterbukuan hati.
“Reza, tak baik cakap macam tu. Buruk-burukpun ayah sendiri kan? Ingat, kasih ayah sepanjang masa. Ayah nak kan yang terbaik untuk
anak-anaknya. Ayah nak anaknya berjaya
dalam pelajaran, dunia akhirat.”
“Reza bukan buat maksiat, main gitar
untuk majlis Hari Guru aja.” Masih mahu
mengadu, menidakkan kesalahannya besar benar.
“Ya, mak tahu. Tapi muzik itu kan menghayalkan? Kalau tak dicantas
minat tu, nanti jadi cita-cita. Ahli
muzik dipandang hina bukan saja di akhirat nanti tapi di dunia juga.”
Diam dia, ada benarnya kata-kata ibu
itu. Memang muzik melalaikan, lihatlah
dia sendiri. Semakin lalai kesibukan
dunia, agak sukar untuk dia berundur.
Pintu bilik ditolak perlahan, meski
perlahan tolakan pintu itu, namun keras benar kenangan semalam terbang. Kembali semangatnya ke seruang bilik kecil
itu. Makcik Rominah menjengah dari luar.
“Tak tidur lagi Reza?”
“Eh, mak? Mak tak tidur lagi?”
Makcik Rominah geleng, senyum
manis. “Boleh mak masuk?”
“Masuklah mak.” Dari duduk di lantai, bersandar pada birai
katil, bangun dia duduk di tepi katil.
“Kenapa tak tidur lagi ni?
Panas?” kipas meja yang sudah lama
rosak, kaku di tempatnya direnungnya.
“Kalau panas, bawak masuk kipas dekat luar tu.”
“Tak mengapa mak, cuaca malam ni tak
berapa panas.”
“Tapi nyamuk banyak, kelambu dah lama
benar tersimpan dalam almari tu, mesti berhabuk. Rafiq pun kalau balik, tak guna kelambu. Dia
guna kipas aja.”
Neor memerhati sekeliling bilik. Memang sejak dahulu di situ banyak nyamuk,
tidak dinafikan. Dan amalan sekampung
itu tidur dikepung kelambu kain yang diikat empat penjuru.
“Nanti mak ambikkan.”
“Tak payah, nanti kalau Reza nak
tidur, Reza ambik sendiri.” Dipegang
tangan Makcik Rominah, ditarik. Tidak
mahu dia menyusahkan wanita itu.
Makcik Rominah angguk, kembali duduk
di tepi katil, berjuntai kaki. “Nanti
pergi ambik ya?”
Neor angguk perlahan. “Mak, mak ikut Reza balik KL?”
“Nak buat apa mak ikut ke sana?”
“Duduk dengan Reza.”
“Nak buat apa?”
“Mak seorang di sini, Reza pun seorang di sana.”
“Tak payahlah, mak sayang rumah ni.”
“Mak tak sunyi ke?”
“Radio ada, tv ada, al-quran ada. Apa
nak sunyi?”
“Tapi Reza nak jaga mak.” Sudah diraih lengan Makcik Rominah, dicangkuk
lengannya, rapat.
“Untuk jaga mak, tak perlu mak duduk
di Kuala Lumpur dengan Reza. Di sini pun
Reza boleh jaga mak, kan?”
“Tapi Reza kerja di sana, di kampung
ni Reza boleh buat kerja apa?”
“Tak apa, Reza duduk sana, sesekali
baliklah.”
“Reza sibuk, jarang-jarang boleh
balik.”
“Tak apa, mak faham. Mak boleh jaga diri sendiri.”
“Mak, Reza sayang mak.”
“Mak pun sayang anak-anak mak.”
“Reza sayang ayah pun.”
“Tak dendam ayah, kan?”
Neor menggeleng. “Tak pernah dendam ayah. Ayah menjalankan tanggungjawabnya. Bukan salah ayah.”
“Alhamdulillah, senang hati mak. Ayah Reza pun tak pernah dendam Reza. Sebelum dia meninggal, ayah kata Reza anak
yang baik. Katanya kalau ada kesalahan
anak-anaknya pada dia, dia dah maafkan.”
Angguk Neor perlahan. “Reza tahu, ayah tak suka Reza jadi pemuzik,
jadi orang seni, tapi mungkin dah takdir, Reza tak dapat mengelak. Reza dah cuba kerja lain, tapi Reza tak
gembira.”
“Ayah Reza pun kata begitu. Katanya, dah puas dia menentang minat Reza
tapi kalau itu juga kecenderungan Reza, ayah redha. Cuma ayah harap, Reza pandai menjaga
diri. Seimbangkan dunia dengan akhirat.”
“Reza janji, Reza akan jaga nama baik
ayah.”
“Bukan nama baik ayah dengan mak,
sayang. Tapi jaga agama. Selagi kita beragama Islam, anak Melayu,
orang Timur pulak, kita dikepung
adat dan adap. Pertahankannya.”
“Ya, insyaAllah, mak.”
“Ha, sembang-sembang ni, mak nak
tanyalah sikit.”
Disambar mata Makcik Rominah, mahu
sangat mendengar apa yang ingin diketahui ibu itu.
“Dah ada calon isteri?”
“Mak….” tertawa dia malu sendiri. “Tak kan Reza nak langkah bendul? Biarlah Rafiq dulu.”
“Mak tanya Rafiq, katanya biar Reza
dulu.”
“Apa pulak adik dulu kahwin daripada
abang?”
“Katanya Reza ada ramai kawan perempuan,
senanglah nak pilih yang mana satu. Apa
namanya? Girl friend?” senyum Makcik Rominah menyebut perkataan
Inggeris itu.
“Mana ada? Kawan perempuan pun tak
ramai, macam mana nak pilih?”
“Betul?”
Angguk dia bersungguh-sungguh.
“ASSALAMUALAIKUM.” Tak tidur lagi Rafiq?” ke bilik Rafiq pula Makcik Rominah.
“Mak?
Masuklah.”
Masuk dia duduk di sisi.
“Mak tak tidur lagi?”
“Belum mengantuk.”
Rafiq sudah bangun dari
pembaringannya. Ditinggikan bantal untuk
dia bersandar.
“Macam mana kerja?”
Rafiq angguk perlahan.
“Sesuai?”
Angguk lagi Rafiq. Jarang mereka berbual mesra kerana Rafiq
jarang mahu memesrakan diri. Jika
pulang, dia lebih gemar menghabiskan masa bersama rakan-rakan di kedai kopi di
pekan selain surau di waktu-waktu solat wajib.
“Kerja tetap dah ada, kereta dah ada,
rumah pun dah beli. Bila lagi nak cari
isteri? Atau anak mak ni dah kahwin senyap-senyap?”
“Hisy, mana ada kahwin? Kalau kahwin
mestilah saya bagitahu mak, bawak calon isteri jumpa mak, kenduri di rumah mak. Tak kan nak kahwin senyap-senyap.”
“Betul, tak akan ketepikan mak?”
“Tidak mak. Selepas ayah meninggal, saya tak ada sesiapa
lagi selain mak.”
“Adik? Rafiq jangan lupa, Rafiq masih ada adik.”
Timbul kucam rona wajahnya, tiba-tiba
tampak benci benar.
“Rafiq, buruk-buruk pun Reza tu adik,
darah daging, dari keturunan sama. Bila
mak pun dah tak ada nanti, Rafiq cuma ada Reza aja. Satu-satunya saudara yang Reza ada.”
“Biarlah kami begini mak. Dia
dengan cara dia, saya cara saya.”
“Kenapa nak berdendam, nak?”
“Saya tak dendam dia, cuma saya tak
nak ada kaitan dengan dia.”
“Sedihnya mak.”
“Kenapa mak nak sedih? Kami bukan
bergaduh, berlengan, bertumbuk pun tak pernah.
Tak macam anak-anak orang lain
yang bercakaran macam anjing dengan kucing.
Cuma kami tak bersefahaman, itu aja.”
Makcik Rominah mengeluh, kecewa lagi
dia. Selaku orang tengah yang berusaha
menanam bunga di tengah-tengah jurang antara Rafiq dan Reza, dia berharap
sekuntum mawar mewangi lalu membiak, menjadi jambatan menghubung antara dua
benua anak-anaknya. Namun jelaslah,
sudah lebih tujuh tahun suaminya meninggal dunia, anak-anaknya kekal bermusuhan
meski tidak pernah bergelut beradu kekuatan kudrat.
Ditinggalkan Rafiq sendiri, seperti
Reza, dia turut menepuk-nepuk dan menggosok anak itu juga. Tidak langsung mahu membanding atau membahagi
kasih. Dia mahu mengisi sama penuh di
dalam sekeping hatinya. Tidak melebihkan
Reza, melebihkan Rafiq juga tidak.




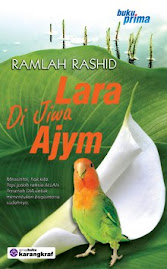




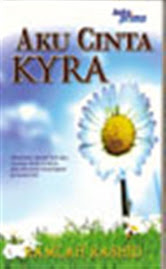.jpg)

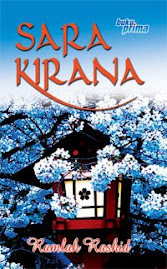
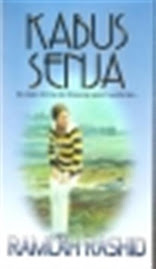+(Large).jpg)

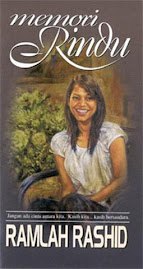.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment